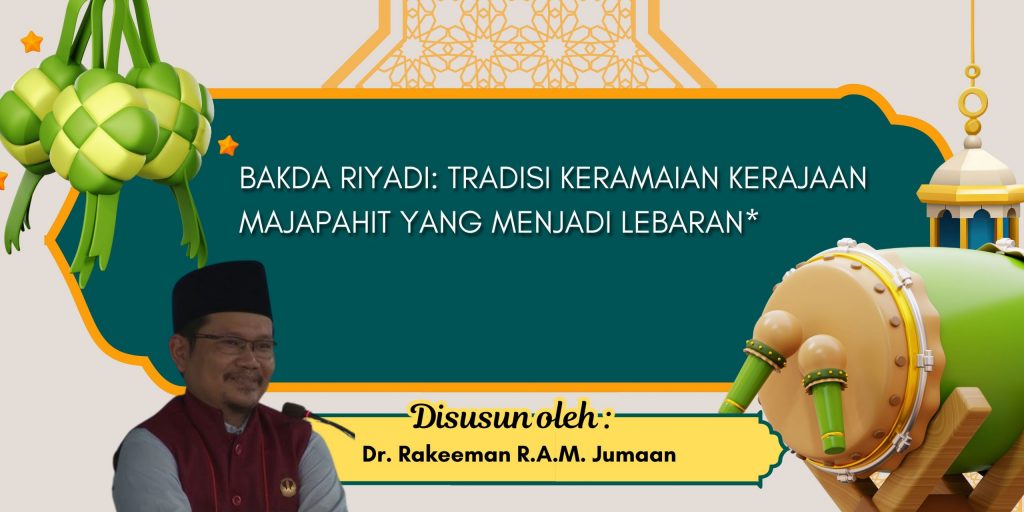PSPPKn Unikama: “Siyam dumuginipun Bakda Riyadi tanggal 1 Sawal ingkang laminipun 11 dintên ngantos tanggal 8 Sawal ingkang ugi dipun wastani Lêbaran Kupat punika kintên-kintên mula bukanipun nêlad saking karameyan ing jaman Majapahit wau.”
Disusun oleh:
Dr. Rakeeman R.A.M. Jumaan**
TRADISI NGABEKTEN DI KELUARGA
Awal tahun 1970 dan akhir tahun 1980, di keluarga besar Sambran –yaitu kakek Penulis dari garis Ayah– masih berlangsung tradisi yang unik. Dibilang unik, karena tidak semua keluarga di Indramayu melaksanakan tradisi ini. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah keluarga Ayah asli dari Indramayu ataukah pendatang?
Pertanyaan ini wajar muncul, sebab tradisi itu tidak umum dilaksanakan di Indramayu. Tradisi yang dimaksud adalah yang dikenal dalam tradisi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Ngabekten. Jenis tradisi apakah itu? Mengapa di Indramayu, tradisi ini dianggap tidak umum alias tidak ada. Jarang sekali atau mungkin saja tidak ada sama sekali keluarga lain yang melestarikan tradisi ini.
Pada saat berkunjung ke rumah nenek dan kakek dari pihak ayah, Penulis harus memberi salam sejak di depan pintu rumah. Lalu, masuk ke dalam ruang tamu dengan bersimpuh (ngesot) mendekati kakek-nenek yang biasanya duduk di kursi ruang tamu, bagian paling ujung dari ruangan itu. Beberapa tokoh pewayangan digantung di dinding bagian belakang mereka.
Setelah berada di depan kakek-nenek kemudian Penulis melakukan sungkem dan ada ucapan yang disampaikan dalam bahasa Jawa halus dan bukan dalam bahasa Jawa Dermayonan. Penulis dan yang lain kemudian duduk bersila di lantai, sementara kakek-nenek tetap duduk di “kursi kebesaran”. Usai tradisi itu, kemudian anak-anak kecil bermain di teras dengan bebas.
TRADISI LEBARAN KUPAT DALAM MANUSKRIP KUNO
Ternyata, tradisi semacam itu telah dibahas dalam manuskrip kuno. Adalah Kanjeng Raden Adipati Aria Krama Djaja Adhi Negara yang menceritakannya dalam manuskrip Bakda Riyadi: Satunggaling Adat Kina. Mantan Adipati Majakerta (Mojokerto) pada masa Belanda itu menuliskan secara rinci sejarah dilaksanakannya tradisi Siyam (Puasa), Bakda Riyadi (Idul Fithri) dan Ngabekten (Sungkeman).
Menurut pencetus lembaga Oudheidkundige Vereeneging Majapahit (OVM) Mojokerto bersama arkeolog Belanda Ir. Henry MacLine Pont itu –yang kemudian menjadi Museum Trowulan–, bahwa Lebaran Kupat meniru tradisi Kerajaan Majapahit, yaitu Nyadran dan Sraddha. Baik dari segi waktu maupun substansi acaranya hampir mirip.
Bila Sraddha dilaksanakan setelah 12 tahun, maka Lebaran Ketupat juga dilaksanakan setelah 11 hari. Lebaran Kupat biasanya dimulai sejak 21 Ramadan hingga 1 Syawal. Lalu, dari 2-8 Syawal dilangsungkan proses tradisi tadi. Keduanya dirayakan dengan hampir sama, yaitu dalam bentuk keramaian (kerameyan).
Secara lebih lengkap, K.R.A. Djaja Kramadjaja Adhi Negara menyebutkan sebagai berikut:
“Jalaran saking cariyos kasêbut ing nginggil wau, Kangjêng Raden Adipati Arya Kramajaya Dinagara, bupati pensiyun ing Majakêrta lajêng kagungan pamanggih bilih wontênipun karameyan ingkang dipunwiwiti ing tanggal 21 wulan Siyam.
Dumuginipun Bakda Riyadi tanggal 1 Sawal ingkang laminipun 11 dintên ngantos tanggal 8 Sawal ingkang ugi dipun wastani Lêbaran Kupat punika kintên-kintên mula bukanipun nêlad saking karameyan ing jaman Majapahit wau. Amila sujarah dhatêng pasareyan ing dintên Bakda Riyadi punika tiyang Jawi amastani: Nyadran. Mila turut pamanggihipun ingkang bupati pensiyunan wau bok manawi inggih saking têmbung: Sradda ing nginggil.”
Dalam buku Album Collections Moens, Ir. J.L. Moens memberikan gambar ilustrasi saat orang melakukan halal-bihalal dengan kerabat, teman, dan sebagainya. Mereka yang muda sowan ke orang yang lebih tua untuk meminta maaf. Dalam hal ini, terjadi juga di lingkungan istana, misalnya di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
KERAJAAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN TRADISI NGABEKTEN
Dalam manuskrip NB 1074 dan KBG 947, yang dilakukan penyalinannya oleh Pigeaud sendiri pada tahun 1934 disebutkan tradisi Ngabekten ini lengkap dengan gambar ilustrasi. Album ini merupakan satu dari 30 album bergambar yang disusun atas prakarsa Ir. Moens di Yogyakarta sekitar tahun 1929-1937.
Di dalam album no. 22 terdapat uraian tentang: 1. Ngabekten (1-10); 2. Jumenengan pangeran Pati (11-25); 3. Jumenengan Pangeran (25-31); 4. Jumenengan Ratu (31-46); 5. Ketik (pasrah) (47-52); 6. Tetesan (sunatan) (53-64); 7. Supitan (tetekan) (65-86); 8. Tingalan dalem (87-110). Naskah aslinya tersimpan di PNRI Jakarta.
Ngabekten ini dilaksanakan juga di kalangan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dimana permaisuri, putra-putri Sultan, Abdi dalem semuanya melakukan tradisi ini. Dengan jelas gambar ilustrasi Ir. Moens memperlihatkannya. Meskipun dengan latar belakang seorang insinyur perairan, Moens ternyata mendalami Javanologi termasuk bahasa dan tradisinya, walaupun tidak sehebat arkeolog lainnya terutama koleganya yaitu Pigeaud.
Ngabekten dilaksanakan setelah Lebaran (bakda Riyadi) atau setelah Grebeg 1 Sawal. Orang-orang yang lebih muda melakukan sungkeman kepada orang-orang yang lebih tua. Seorang istri melakukan ngabekten kepada suaminya, begitu juga anak-anak kepada ayahnya. Para abdi dalem atau pelayan melakukan ngabekten kepada Raja atau majikannya.
TRAH LELUHUR DARI MATARAM ISLAM?
Membandingkan dengan tradisi yang dilakukan di Jawa Tengah khususnya Mataram Islam atau kini Ngayogyakarta Hadiningrat, dengan tradisi keluarga dari pihak Ayah di Indramayu, ada hubungan samar antara Mataram Islam dan leluhur dari garis Ayah.
Pertama, Indramayu sejak awal merupakan wilayah terjauh Kerajaan Mataram Islam. Oleh sebab itu, Adipati pertama Indramayu berasal dari Bagelen (Pusat Mataram Islam), yaitu Wiralodra, 1627. Wiralodra ditugaskan untuk mengamankan wilayah paling barat dari kemungkinan serangan VOC.
Kedua, serangan pasukan Mataram Islam ke Benteng Hollandia Batavia terjadi dua kali. Serangan pertama dilakukan pada 1628, sedangkan serangan kedua pada 1629. Pasukan Dipati Ukur melakukan serangan dari arah Bandung menuju Batavia. Namun, kedua serangan tersebut gagal menembus Benteng pertahanan VOC. Pasukan Mataram dikagetkan oleh senjata modern VOC, yaitu meriam.
Dalam serangan ke Batavia tersebut, Mataram Islam dibantu oleh Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Serangan pertama (1628) gagal menghancurkan VOC. Dua orang panglima perang Mataram Islam, yaitu Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Mandurareja disertai sekitar 10 ribu prajurit tidak mampu menerobos benteng Hollandia di Batavia. Akibat kekurangan perbekalan, mereka menjadi lemah dan kalah. Sultan Agung kemudian mengirim algojo untuk memberi sanski prajurit yang kalah itu.
Sebagian prajurit kemudian menetap di sepanjang Pantura dan menikah dengan wanita setempat. Di Pantura, atas usul Nyi Ageng Tirtayasa, penasihat Sultan Agung Hanyakrakusuma alias Susuhunan Sultan Agung Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman alias Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram mulai dibuka pesawahan sebagai bekal perang.
Serangan kedua dilakukan setahun kemudian, 1629. Serangan ini dipimpin oleh Adipati Ukur dan Adipati Juminah dengan kekuatan 14 ribu prajurit. Belajar dari kekalahan serangan pertama, Mataram Islam membuat lumbung-lumbung padi di sepanjang jalur Pantura Jawa Barat yaitu antara Cirebon-Indramayu-Cikampek. Namun, serangan kedua juga gagal menghancurkan VOC di Batavia.
Dari dua hal ini, cukup sebagai bukti bahwa pasukan Mataram Islam, banyak yang kemudian tinggal di sepanjang Pantura, mulai dari Karawang, Cikampek, Subang, Pamanukan, Eretan, Karangsinom, Losarang, Lohbener dan lokasi lainnya. Setelah beberapa generasi, mereka kemudian menjadi bertambah banyak.
Ketiga, saat dilakukan tanam paksa (cultuurstelsel) oleh Belanda pada 1830, kawasan Pantura yang dikenal sebagai Wirasaba kemudian menjadi kawasan pertanian (land/onderneming) terutama komoditas padi dan tebu. Saat itulah, penduduk yang merupakan keturunan prajurit Mataram Islam itu kemudian disebar lagi ke beberapa lokasi. Termasuk, leluhur Ayah yang tadinya tinggal di kawasan pantai kemudian pindah sekitar 15 kilometer ke perkampungan di Blok Rong, dekat Cikabuyut Rong.
Keempat, pada masa Belanda (1800-1942) dan Jepang (1942-1945), karena leluhur Ayah berasal dari keluarga tuan tanah (landlord/landheer), maka Ayah bisa ikut mengenyam pendidikan di sekolah rakyat (SR) tiga tahun. Hanya sedikit anak pribumi yang saat itu bisa sekolah, khususnya anak pejabat dan tuan tanah.
Kelima, Ayah memiliki empat orang istri dan total 11 anak dari keempat istrinya. Ibu Penulis merupakan istri keempat. Artinya, hanya orang yang berasal dari strata tinggi yang melakukan hal itu. Biasanya, tuan tanah atau keturunan tuan tanah atau pejabat/anak pejabat yang melakukan hal ini. Sangat sulit dan merupakan suatu anomali bila penduduk biasa dapat melakukan hal ini. Salah seorang istri Ayah, setelah dicerai, kemudian dinikahi oleh Ketua Jemaat Ahmadiyah Sekarmulya (Indramayu) pertama. []
Pendhawa Mulat Sirnaning Penganten!
Catatan:
*) Selesai ditulis pada Senin, 31 Maret 2025 pkl. 21:00 WIB di Rumah Dinas Griya Carani “DAAR EL-JUMAAN” Bogor, Jawa Barat.
**) Penulis merupakan Ikon Prestasi Pancasila 2021 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Jakarta, yang juga Direktur dan Pengulik pada Pusat Kajian Manuskrip Islam dan Filologi (Centre for the Study of the Islamic Manuscripts and Philology) Ambon, Maluku dan Pembina Nasional Forum Mahasiswa Studi Agama-Agama se-Indonesia (FORMASAAI) dan Pembina Nasional Forum Mahasiswa Ushuluddin se-Indonesia (FORMADINA). []